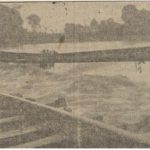Jika Sartono Kartodirdjo masih hidup hari ini, saya berharap ia menjewer para sejarawan yang hari ini berkelakuan nakal. Mereka dijewer bukan karena keliru dalam menulis sejarah, melainkan karena memilih diam.
Di tengah polemik penulisan ulang sejarah nasional, para sejarawan senior, yang begitu lantang di ruang-ruang akademis, justru absen dari ruang publik. Mereka bertengger nyaman di atas menara gading, ketika sejarah kembali diperlakukan sebagai proyek para penguasa.
Mungkin mereka menganut prinsip “diam itu emas.” Tetapi, diam ketika sejarah menjadi senjata penguasa untuk menyebarkan apa yang dianggap benar dan dirasa salah, itu bukanlah emas. Itu justru bentuk dari kenakalan intelektual.
Tulisan ini merupakan keresahan hati, sekaligus kekecewaan, terhadap kehidupan sejarah di Indonesia saat ini.
Kekecewaan
Apa yang saya rasakan terkait para sejarawan nakal, bukan sekadar persoalan pribadi. Sebagai seorang sejarawan muda, yang mungkin belum pantas disebut sejarawan, saya bergidik juga mendidih ketika mendapati kesejarahan di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius.
Di tengah kebimbangan lulusan sejarah, baik keilmuan maupun pendidikan, dalam mengarungi pasar ketenagakerjaan, para penguasa mengobok-obok historiografi dengan menerbitkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Meski sempat menghadapi tekanan dan kecaman publik, pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, tetap jalan terus menyelesaikan proyek ini.
Yang membuat saya kesal, adalah para dosen yang saya kenal kritis di ruang kelas, tampak tak bersuara. Saya masih belum menemukan kritik mereka, baik di media cetak maupun daring. Bahkan, sesederhana berkomentar di media sosial pun, saya rasa hanya beberapa yang bersuara.

Saya membayangkan kegelisahan terkait kondisi kesejarahan di negeri ini akan memunculkan polemik seperti Soedjatmoko dan Bojoeng Saleh, yang saling berbalas argumen di media. Atau, mundur sedikit lebih jauh, antara BM Diah dengan Njoto, yang dapat diikuti publik kala itu.
Ketiadaan polemik dalam kasus proyek sejarah nasional pemerintah, seakan-akan menampilkan jurang yang menganga antara sejarawan senior (istilah saya bagi para dosen, akademikus, dan sejarawan yang otoritatif) dengan masyarakat. Para sejarawan senior memilih untuk tidak mau banyak komentar, dan lebih nyaman bertengger di tempat yang telah membuat mereka tenang: menara gading.
Diliputi kekecewaan, saya mengatakan bahwa sikap sejarawan senior yang demikian tidak menunjukkan komitmen moral dan kepedulian sosial. Saya begitu menantikan diskusi antarsejarawan, seperti yang dilakukan Bambang Purwanto (seterusnya ditulis BP) dengan Asvi Warman Adam terkait gagasan pelurusan sejarah dalam buku Menggugat Historiografi Indonesia.
Sejak Sartono Kartodirdjo menawarkan pendekatan baru dalam menulis sejarah, seharusnya ada angin segar dalam proses membangun historiografi Indonesia, termasuk menumbuhkan budaya kritis antarsejarawan dan antara sejarawan dan masyarakat. Sayang, ia hanya berakhir sebagai kekecewaan semata.
Bertengger di Menara Gading
Selama ini, saya mendengar diskusi sejarah yang dilakukan di ruang kelas tampil berapi-api. Segala pembahasan tentang metode, metodologi, kritik sumber, hingga perspektif dalam rekonstruksi sejarah, dikuliti habis-habisan.
Namun, saat keluar kelas, omongan yang serba ndakik-ndakik ini menguap tanpa jejak. Terlebih, ketika menghadapi polemik penulisan ulang sejarah Indonesia tahun lalu, ia tak menghasilkan jejak yang bisa saya temui.
Di lingkungan akademik, ilmu sejarah diajarkan sebagai disiplin yang ketat dan penuh kehati-hatian. Para sejarawan senior menekankan nilai penting metodologi yang ketat dalam menulis masa silam. Sejarah terus diperdebatkan sebagai satu konstruksi yang selalu terbuka, membuat eksistensi narasi tunggal selalu berakhir dengan kecurigaan.
Sayang seribu sayang, diskusi penuh akrobatik ini hanya berakhir di ruang kelas, jurnal ilmiah, hingga seminar di lingkungan kampus. Saat isu penulisan sejarah nasional mencuat, sejarawan senior enggan untuk unjuk taring, menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Sikap demikian, seolah-olah menciptakan jarak antara ruang akademik dan ruang publik.

Jarak tersebut akhirnya diisi oleh sejarawan amatir. Melalui berbagai konten, sejarah menjadi lebih mudah untuk dinikmati, dan kemudian didiskusikan publik. Mereka mengisi dahaga publik yang begitu haus akan masa silam.
Namun, kehadiran sejarawan amatir bukan berarti kesadaran sejarah terlahir. Konten yang mereka terbitkan sering kali tidak berangkat dari metodologi yang kuat. Ini membuat mereka sering mengabaikan konteks sejarah, menyederhanakan persoalan, hingga terjebak dalam bias perspektif.
Meski begitu, mereka akhirnya menjadi rujukan publik terhadap pengetahuan masa silam. Sejarawan senior, yang begitu nyaman duduk di ruang kerjanya, absen dalam kegiatan ini. Hasil akhir, mudah untuk ditebak: pengetahuan akan peristiwa di masa lampau dihasilkan oleh mereka yang bersedia mengisi, meski tanpa kemampuan kesejarahan yang kuat.
Pesimisme akan Masa Depan yang Menghantui
Refleksi ini berangkat dari realita, bahwa lulusan sejarah hanya bisa menelan pil pahit di negeri ini. Selain karena harus menghadapi lapangan kerja yang begitu sempit, mereka juga harus berkutat melawan ekosistem yang begitu keras.
Mereka hidup dalam bayang-bayang masa depan, yang tampak tak kunjung cerah. Dalam bahasa Kuntowijoyo dalam buku Metodologi Sejarah (Edisi Kedua), ia merupakan pesimisme yang berlebihan akan masa depan.
Dulu, saya hanya membaca sepenggal kalimat ini. Sekarang, saya merasakan kehadirannya. Meski sejarah terus dikembangkan di perguruan tinggi, materi dan metode pembelajaran nyaris tak berubah, ketika tantangan zaman terus bergeser. Sejarah tampak sebagai catatan masa lalu yang begitu jauh, tak lagi memberikan gambaran jelas tentang bagaimana ia dapat membantu mereka menghadapi masa depan.
Kondisi demikian diperparah ketika para lulusan muda harus menampilkan sejarah kritis di luar ruang kelas. Pesimisme berlebihan berbuah pada dangkalnya pemahaman sejarawan muda untuk ikut berdiskusi di tengah masyarakat.
Di satu sisi, masyarakat ingin mendapatkan pengetahuan sejarah yang menarik. Di sisi lain, sejarawan muda lulusan universitas masih kesulitan untuk mengisi keinginan tersebut, dan bahkan menempatkan sejarah terkait kembali dengan berbagai kondisi kontemporer yang terjadi saat ini. Sejarah akhirnya tampil di masa lalu, dan sejarawan muda serta publik kehilangan motivasi untuk mendalaminya.
Menghadapi kondisi suram ini, Sartono Kartodirdjo, bapak bagi semua sejarawan di negeri ini, telah lama hadir dalam bentuk konstruksi historiografi Indonesia yang menekankan analisis kritis, keterbukaan pada diskusi publik, serta menempatkan sejarah agar relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita ingat akan kehadirannya?