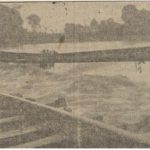Kemajuan teknologi, membantu upaya sejarawan dalam melukis masa silam dengan wajah baru. Hal tersebut diwujudkan melalui upaya digitalisasi, utamanya surat kabar.
Sebagai salah satu sumber penting untuk menyelami kehidupan masyarakat pada masa lampau, surat kabar dapat membantu kerja sejarawan dan pembuat arsip. Bagi kelompok yang disebut terakhir, mereka dapat mengkliping artikel, berita, maupun iklan yang terbit dalam sebuah surat kabar dengan lebih inklusif dan minim biaya.
“Ini adalah sebuah anugerah besar,” demikian cara saya mengungkapkan kehadiran digitalisasi surat kabar ini. Ia bisa menjadi sumber pembanding, memberikan pandangan berbeda atas hasil rekonstruksi sejarah yang sudah diterima umum.
Ketika saya sedang mengumpulkan surat kabar lama di Delpher, saya tak sengaja menemukan sebuah surat kabar terbitan Belanda, Nederlands dagblad. Surat kabar tersebut terbit pada 22 Agustus 1991, memuat satu tulisan yang membuat mata saya tak mampu berkedip.
Tulisan itu berjudul Papua’s zijn Melanesiers en horen niet bij Indonesie (Orang Papua adalah Melanesia dan bukan bagian dari Indonesia), ditulis Wim Conraadts. Pada bagian awal, Conraadts melukiskan secuil kisah awal integrasi masyarakat Papua ke dalam Indonesia. Ia menyebut itu sebagai frauduleuze volksraadpleging alias “referendum yang curang.”

Istilah tersebut, hingga kini menjadi titik persoalan yang belum menemui titik terang di Indonesia. Pasca-referendum tersebut, ketegangan dan kekerasan struktural masih berlanjut. Pada hari ini, konflik Papua sejatinya patut dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Laurens Ikinia dalam Transformasi Konflik Menuju Damai, konflik Papua tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang sederhana. Misalnya, yang umum terjadi kini, konflik itu sering dilihat sebagai perlawanan pasukan NKRI dengan pasukan separatis semata.
Lebih lanjut, Laurens Ikinia menerangkan bahwa konflik Papua perlu ditangani dengan pendekatan keamanan yang humanis. Dengan demikian ia perlu ditangani secara lebih bijak.
Setelah selesai membaca habis tulisan itu, saya mendapatkan kesimpulan bahwa suara masyarakat Papua tidak hanya bergema di Indonesia. Ia juga eksis di Negeri Kincir Angin itu.
Ini tidak terjadi begitu saja. Ketika masyarakat Papua menolak untuk bergabung dengan Indonesia dan memilih merdeka setelah integrasi, Organisasi Papua Merdeka (OPM) lahir, sebagai upaya untuk memerdekakan Papua dari cengkeraman Indonesia.
Mengutip artikel Proklamasi 1 Juli 1971 dan Gerakan Militer Papua Barat, organisasi ini bermula dari sisa pasukan Papoea Vrijwilligers Korps (PVK), yang dipersiapkan untuk penentuan nasib sendiri. Namun, pada 1 Mei 1963, ia dibubarkan.
Beberapa mantan pasukan PVK kemudian merangkul beberapa OAP untuk melanjutkan perjuangan pembebasan. Pada 1 Juli 1971, Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM) dibentuk, yang kini dikenal dengan nama OPM.
Bagi Jakarta, OPM merupakan pemberontak yang mengancam kedaulatan NKRI. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana negara menyebut pasukan pembebas ini sebagai Organisasi Papua Merdeka, yang semula dipandang sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Seperti yang diungkapkan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mereka akan menindak tegas OPM, dengan dasar tidak boleh ada negara di dalam negara.
Terlepas dari kepentingan politik Conraadts, maupun Belanda secara umum, terkait isu Papua, tulisannya memantik rasa penasaran saya. Apa yang setidaknya bisa kita selami dari tulisan dalam Nederlands Dagblad ini?
Melihat Ke Belakang
Jika kita mundur ke belakang, kita akan menemukan berbagai kisah di balik proses integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa Papua adalah bekas jajahan Belanda, yang meski berbeda secara kultural, sama-sama ditindas oleh penjajah kulit putih itu.
Setidak-tidaknya, kita bisa menarik sejak Konferensi Meja Bundar (KMB), pada 2 November 1949. Kala itu, hak atas wilayah Irian Barat menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Perdebatan pun terjadi.
Mengutip buku Pasang Surut Sejarah Papua dalam Pangkuan Ibu Pertiwi, pihak Indonesia menilai bahwa Belanda akan melanjutkan kolonialisme atas Irian Barat. Namun, pihak Belanda berdalih tentang bahaya neo-kolonialisme, yang akan menjadikan orang-orang Papua akan diperbudak pemerintah Indonesia di kemudian hari.
Satu hal yang pasti, mengutip Yuda Prinada dalam artikel Sejarah Operasi Trikora: Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh, kedua belah pihak merasa paling berhak atas kepemilikan Irian Barat.

Karena tidak menemui titik terang, KMB memutuskan bahwa nasib Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun berikutnya. Namun, sampai 12 tahun berlalu, permasalahan tersebut tak kunjung tuntas.
Menurut Petrik Matanasi dalam artikel Sejarah Pidato Trikora dan Ambisi Soekarno Kuasai Papua, alasan mengapa Belanda tidak juga kunjung menyelesaikan permasalahan ini, adalah karena ia ingin membangun Irian Barat sebagai negara boneka. Ini terlihat dari upaya mereka memperkuat Papua.
Pada 1961, Belanda memilih anggota parlemen baru, dan membentuk Komite Nasional Papua. Langkah tersebut direspons oleh Soekarno pada 19 Desember tahun yang sama, dengan meluncurkan Operasi Trikora, di bawah pimpinan Mayjend Soeharto.
Konflik antara Indonesia dan Belanda atas tanah Irian Barat, tak kunjung usai hingga 1962. Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Perjanjian New York ditandatangani.
Melalui perjanjian ini, wilayah sengketa berada di bawah otoritas eksekutif sementara PBB (United Nations Temporary Executive Authority) mulai 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963. Kemudian, Irian Barat diserahkan kepada Indonesia, dengan catatan mereka harus mengadakan pemungutan suara pendapat rakyat (Penentuan Pendapat Rakyat/Pepera) pada 1969.
Seperti yang diungkapkan Oktovianus Pogau dalam artikel Pepera 1969 dalam Perspektif Kaum Muda Penuh Rekayasa dan Manipulatif (dalam buku Narasi Sejarah Sosial Papua: Bangkit dan Memimpin Dirinya Sendiri), Pasal XXII dalam Perjanjian New York menyatakan bahwa sistem one man, one vote yang diterapkan dalam pemungutan suara.
Namun, ia meninggalkan banyak manipulasi, yang akan terang pada bagian berikutnya.
Manipulasi, Intimidasi, dan Rekayasa dalam Integrasi
Seharusnya, 800.000 penduduk Papua dilibatkan dalam proses Pepera pada 1969. Namun, menurut Socrates Sofyan Yoman dalam artikel Akar Konflik Papua: Sengketa Pepera 1969, Pemerintah Indonesia hanya melibatkan 1.025 masyarakat Papua dan non-Papua untuk memilih.
Selain itu, setiap penduduk Papua yang ikut dalam Pepera harus menjalani karantina oleh militer Indonesia selama tiga bulan. Dalam karantina ini, mengutip Yoman, mereka dipaksa untuk memilih Indonesia. Bahkan, militer Indonesia tak segan-segan akan membunuh mereka, jika tidak memilih untuk bergabung dengan Indonesia.
Seperti yang sudah ditebak, Pepera menetapkan Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Dengan cepat, pemerintah Indonesia mulai mendorong program transmigrasi di tanah Papua. Seperti yang diungkapkan Conraadts, para petani di tanah Jawa yang tidak memiliki tanah, dikirim ke Papua, dan diberikan sebidang tanah.

Ketika para petani dari Jawa tiba di Papua, tanah-tanah milik masyarakat adat di Papua dinyatakan tidak sah oleh pemerintah Indonesia, dan diberikan kepada para transmigran. Bagi pemerintah Jakarta, masyarakat adat di Papua tidak memiliki dokumen resmi atas kepemilikan tanah mereka. Hal ini merenggut sumber daya paling berharga bagi masyarakat adat di tanah Papua.
Conraadts mencatat kisah tersebut sebagai berikut:
“[p]olitik pemukiman dan pertanahan ini merupakan duri dalam daging bagi orang Papua. ‘Pihak berwenang menetapkan lahan pertanian yang merupakan milik suku bagi para transmigran’, jelas Sawor. ‘Orang Papua tidak dimintai pendapat apa pun, tapi mereka harus meninggalkan lahan pertanian tradisional mereka. Orang Papua tidak menanam tanaman mereka (termasuk ubi jalar dan ubi) di lahan tetap’.”
Menghadapi jawanisasi atas tanah mereka, masyarakat Papua menyuarakan protes kepada pemerintah Indonesia. Namun, ketika suara mereka mati di tanah sendiri, ia justru menggema di negeri Belanda.
Tuntutan dalam Protes
Di Belanda, masyarakat Papua melancarkan protes sejak 1970-an. Tuntutan utama mereka adalah program transmigrasi pemerintah Indonesia, yang mereka anggap sebagai likwidatie van de Papua natie (likuidasi bangsa Papua).
Bagi pemerintah Indonesia, proyek transmigrasi Orde Baru, utamanya di tanah Papua, merupakan sebuah keberhasilan. Seperti yang diungkapkan mantan ketua Fraksi Golkar, Robert J. Kardinal, ia tidak hanya membangun ekonomi Papua, tetapi juga menciptakan nation building, mempererat tali persaudaraan sebangsa dan memperkuat kehadiran negara di wilayah yang jauh dari Jakarta.
Namun, apa benar demikian? Mengutip Indira Ardanareswari dalam artikel Sejarah Transmigrasi Orang Jawa ke Papua, program yang dicanangkan Soeharto tersebut justru menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Papua. Mereka menganggap pemerintah pusat ingin merebut tanah mereka dengan cara meng-indonesia-kan Papua.

Dengan mengutip buku The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues and Approaches tulisan Esther Heidbüchel, Ardanareswari mengatakan bahwa pemerintah Jakarta berusaha menetapkan standar hidup dan kebudayaan ala Jawa di tanah Papua. Mereka dipaksa untuk mengikuti kemauan Jakarta alih-alih memberdayakan pengetahuan lokal mereka, mulai dari pendidikan, cara memproduksi pangan, dan lainnya.
Melihat kondisi demikian, masyarakat Papua menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. Hal ini, memperkuat suara mereka, baik di Papua maupun di Belanda, yang kemudian dipahami sebagai perlawanan oleh pemerintah Jakarta.
Suara-Suara yang Terpinggirkan
Kini, suara masyarakat Papua di Belanda menunjukkan bahwa mereka eksis, dan berusaha mempertahankan identitas, kebudayaan, dan tanah mereka. Meski Jakarta melihat mereka sebagai pemberontak, dan masyarakat di luar Papua memahami mereka sebagai kelompok separatis dan anti-NKRI, mereka terus bersuara lantang.
Seperti yang diungkapkan Conraadts, masa depan untuk Papua yang mandiri:
“… mungkin terletak dalam federasi dengan kelompok pulau di sekitarnya di kawasan Pasifik. ‘Kami bukan orang Asia; kami orang Melanesia. Sebagai negara merdeka, kami harus lebih fokus pada Papua-Nugini, Fiji dan Kepulauan Solomon, dan Vanuatu serta membentuk federasi dengan negara-negara ini’, demikian kesimpulan Sawor.”
Apa yang bisa kita pahami dari artikel kecil di satu surat kabar Belanda ini? Satu hal, bahwa permasalahan di tanah Papua bukanlah soal “pahlawan” dari Jakarta melawan “pemberontak” yang bergerilya di hutan. Ia adalah suara masyarakat Papua, yang terjajah di negerinya sendiri, dan hingga kini dianggap tidak ada oleh Jakarta.