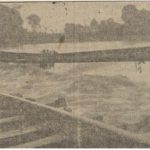“Woi! Kakak dulu juga begini! Bahkan, lebih parah!”
Bagi mahasiswa saat ini, mungkin sudah asing mendengar kalimat seperti di atas. Mengingat, sistem orientasi mahasiswa baru (maba) sudah berganti menjadi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), menggantikan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK).
Pergantian nama program orientasi mahasiswa baru tersebut, adalah upaya pemerintah untuk menghilangkan budaya kekerasan, baik fisik, verbal, dan seksual, serta senioritas, dalam kegiatan itu. Mengikuti panduan yang diterbitkan Direktorat Pembelajaran dan KemahasiswaanKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, panitia PKKMB dilarang untuk melakukan kekerasan verbal dan/atau fisik kepada mahasiswa baru.
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, alasan pergantian nama menjadi PPKMB adalah karena adanya niat dari para pemangku kebijakan untuk menghapus budaya kekerasan dalam proses orientasi mahasiswa baru. Budaya kekerasan tersebut, dikenal sebagai perpeloncoan.

Meski kini telah berganti nama, budaya pelonco, yang membekas ketika masih bernama OSPEK, tetap ikut terbawa. Seperti yang ditulis oleh Tempoco, setidak-tidaknya terdapat tujuh kasus selama PPKMB pada 2023, dengan berbagai penyebab.
Lebih lanjut, pada tahun yang sama, terjadi kasus perpeloncoan yang dilakukan mahasiswa Jakarta Global University. Para mahasiswa baru dipaksa untuk terjun ke kubangan lumpur. Kasus tersebut berakhir ditangani oleh pihak berwajib.
Mengapa ini masih terus terjadi?
Ontgroening, Cikal Bakal Perpeloncoan
Budaya perpeloncoan, atau bentuk kekerasan lain dalam orientasi mahasiswa baru, dapat dilacak dari Belanda, negara yang mengimpor tradisi tersebut ke Indonesia.
Di Belanda, ia dikenal sebagai ontgroening, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai inisiasi. Ontgroening dapat dimaknai sebagai sebuah awalan bagi seorang mahasiswa atau seseorang yang masih hijau (groen), sebelum ia dapat bergabung dalam kampus/kelompok tertentu. Di Indonesia, kata ontgroening dikenal dengan istilah perpeloncoan.
Sebagai sebuah proses inisiasi, anggota lama (senior) “menyambut” anggota baru (yunior) ke dalam dunia mereka. Dalam riwayat awalnya, tepatnya di Belanda pada abad ke-17, ontgroening dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti pemalakan dan “ejekan di jalan.”
Di Hindia Belanda, kondisi serupa juga terjadi dalam praktik ontgroening. Dilansir dari berita De Locomotief, seorang siswa di Semarang dikeluarkan dari sekolah karena ia berperilaku berlebihan ketika sedang memelonco siswa lain. Rupanya, dalam berita yang sama, pelaku perpeloncoan tidak seorang diri, tetapi dilakukan secara berkelompok.

Meski merupakan sebuah kegiatan inisiasi, ontgroening tak lepas dari kekerasan, baik fisik maupun verbal. Hal ini, yang kemudian mengalami penolakan oleh beberapa kalangan.
Mengutip literatur bertajuk Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven, terdapat sebuah dekret yang melarang praktik ontgroening di Universitas Franeker pada 1601. Pada halaman 122 literatur tersebut, para siswa yang masih groen “dicemooh di jalanan dan dilecehkan di kuliah-kuliah.” Ada siswa lain yang melindungi mereka, meski ia berakhir “merampok” dompet para groen yang menderita itu.
Di Hindia Belanda, kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi. Seperti yang dikenang Mohammad Roem saat bersekolah di STOVIA, praktik ontgroening begitu meresahkan. Keresahan ini, kemudian mengusik Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), untuk melawan praktik ontgroening.
Merasuk dalam Ruang Militer dan Sipil
Di Indonesia, ontgroening dimaknai dengan kata perpeloncoan, lengkap dengan membawa tradisi kekerasan dan senioritas yang melekat dalam proses inisiasi. Ia merasuk di Indonesia dalam ruang sipil dan militer.
Dalam ruang militer, mengingat struktur dalam kemiliteran yang begitu tegas, budaya perpeloncoan tidak dapat dihindarkan. Budaya ini bisa dibagi menjadi tiga, yakni fisik, militer, hingga seksual.
Secara fisik, perpeloncoan dalam dunia militer melibatkan hukuman fisik. Hal tersebut meliputi push up, pemukulan, hingga dipaksa membawa beban berat. Seperti yang terjadi pada Prajurit Dua (Prada) Lucky Saputra Namo yang berpangkat, yang dianiaya oleh seniornya hingga meninggal.
Selanjutnya, wujud perpeloncoan secara mental dalam lingkup militer meliputi hinaan secara verbal. Meski tidak begitu terlihat, kekerasan seperti ini begitu berbahaya. Terkadang, apa yang telah dirabatkan bisa berakhir petaka, seperti yang dialami Joseph A. Felix, seorang drill sergeant yang mengucapkan kata-kata tak pantas, seperti “ISIS” dan “teroris,” kepada yuniornya yang beragama Islam.
Terakhir, ruang militer memberikan kesempatan untuk melakukan perpeloncoan secara seksual. Hal ini meliputi sentuhan terhadap area tubuh yang privat, hingga pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Contoh dekat tentang ini, adalah kisah Prada Lucky, yang selain mengalami kekerasan fisik, juga mengalami kekerasan seksual dalam bentuk olesan cabai di area privat.

Kondisi perpeloncoan dalam dunia militer tidak hanya dialami oleh yunior, dalam arti mereka yang masih groen. Omar Dani, seorang petinggi militer yang disegani pada masa Soekarno berkuasa, sempat menjadi bulan-bulanan para seniornya. Ketika ia menduduki posisi Panglima KOLAGA (Pangkolaga), Pangdam Mulawarman, Soemitro, menyebutnya sebagai bocah kemarin sore.
Selain dirinya, Soeharto, yang kelak menjadi Presiden kedua RI, sempat bergesekan dengan Omar Dani. Ketika keduanya pernah bekerja bersama-sama saat Konfrontasi, dengan Soeharto sebagai Wakil Panglima KOLAGA, ia berpendapat bahwa Omar Dani kurang tepat menjabat posisi panglima KOLAGA. Ini membuatnya “membandel,” melakukan berbagai hal yang semula ditolak Omar Dani, seperti dalam bidang strategis dan lainnya.
Lalu, bagaimana tradisi perpeloncoan dalam dunia sipil? Berbeda dengan ruang militer yang cenderung “keras,” kondisi dalam ruang sipil dapat dikatakan “lebih lunak.” Dalam ruang sipil, perpeloncoan eksis dalam bentuk fisik dan verbal.
Satu contoh menarik adalah proses perpeloncoan yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada 1952. Mengutip rubrik Tahukah saudara? dalam harian Suara Indonesia edisi 22 Oktober 1952, mereka diminta menarik dokar sepanjang jalan Malioboro, agar “punja rasa sajang kepada binatang.”
Lebih lanjut, harian Indische Courant pada 15 Agustus 1941 mengabarkan adanya praktik perpeloncoan oleh mahasiswa senior Nederlandsch-Indische Artsen School (NIAS) dan School Tot Opleiding van Indische Tandartsen (STOVIT) terhadap mahasiswa baru. Perpeloncoan tersebut berlangsung selama lebih kurang dua minggu, dari 16 hingga 31 Agustus 1941.
Kini, ketika NIAS dan STOVIT berubah menjadi Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, kekerasan dalam orientasi mahasiswa baru masih terjadi. Seperti yang diungkapkan seorang rekan yang pernah mengikuti proses inisiasi pada 2023, praktik marah-marah dan membanting pintu masih terjadi.
Nama Berganti, Tradisi Tetap Terwariskan
Melihat budaya kekerasan dalam perpeloncoan, desakan dari publik untuk mereformasi kegiatan inisiasi mahasiswa baru, utamanya di ruang sipil, semakin menguat.
Berkaca dari riwayat kekerasan dalam perpeloncoan di Indonesia, harian Kompas edisi 21 Agustus 1996 (dikutip melalui situs Hai) mengabarkan kisah Heriyanto, mahasiswa baru Universitas Hasanuddin (UNHAS), menjadi korban perpeloncoan. Ketika ia sedang mengembalikan biodata ke fakultas, para senior menendang, menampar, dan mendorongnya. Kekerasan ini mengakibatkan Heriyanto mengalami luka di kepala sehingga harus mendapat tiga jahitan.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 2003, kekerasan dalam kegiatan perpeloncoan kembali terjadi. Wulandari, mahasiswa UNHAS, ditemukan meninggal di kamar indekosnya. Diduga, ia mengalami kelelahan saat mengikuti kegiatan OSPEK, dan membuat penyakit jantungnya kambuh.
Kisah kekerasan di UNHAS tidak berhenti sampai di sini. Dua tahun kemudian, Ade Chandra dan Putri, mahasiswa baru di kampus tersebut, mengalami kekerasan saat kegiatan pra-OSPEK. Kedua mahasiswa ini berakhir dilarikan ke rumah sakit, akibat kekerasan yang mereka alami.
Kekerasan dalam kegiatan inisiasi mahasiswa yang masih groen mencapai puncaknya, Fikri Dolasmantya Surya, mahasiswa Jurusan Planologi, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, meregang nyawa di tangan para seniornya saat melakukan Orientasi Kemah Bakti Desa di kawasan Goa Cina, Malang.
Seperti yang dikisahkan seorang rekan Fikri, para senior melakukan berbagai tindak kekerasan, baik fisik maupun seksual, kepada Fikri dan rekan-rekannya. Dikutip melalui pemberitaan Kompas.com, J, rekan Fikri, mengatakan:
“Peserta diinjak-injak saat disuruh push-up. Lalu dipukul pakai sandal dan benda lainnya yang dipegang panitia. Ada teman lainnya yang disuruh berhubungan layaknya suami sitri[sic]. Tetapi, antara sesama laki-laki. Bukan perempuan dan laki-laki.”
Merespons kematian Fikri, mahasiswa ITN Malang, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK), menggelar aksi unjuk rasa. Selain menuntut keadilan, mereka menuntut pihak kampus bertanggung jawab atas kejadian ini. Pihak kampus turun tangan, dan menjatuhkan sanksi akademik kepada tiga orang panitia kegiatan tersebut.
Berbagai kisah kekerasan, yang terkadang berujung kematian, membuat publik gerah. Anies Baswedan, yang saat itu merupakan akademikus Universitas Paramadina, menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang terjadi dalam proses inisiasi mahasiswa baru. Baginya, budaya kekerasan dalam kegiatan ini adalah tindakan primitif, utamanya jika tradisi masa lalu tersebut masih dilanggengkan hingga kini.
Tidak hanya Anies yang bersuara. Dalam situs Liputan Kampus milik Sekolah Teknik Tinggi Garut (kini Institut Teknologi Garut), sang penulis menyebut bahwa budaya kekerasan dalam inisiasi mahasiswa baru sering dipandang sebagai upaya untuk menciptakan sikap disiplin.
Alih-alih membangun budaya disiplin, ia sering berakhir sebagai ajang balas dendam para senior kepada juniornya. Dalam bahasa lain, Tika Bisono menyebutnya sebagai degradasi nilai kemanusiaan.
Keresahan publik ini, membuat pemerintah turun tangan. Saat menjabat posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan menerbitkan surat edaran, untuk memastikan tidak ada kekerasan yang terjadi dalam proses masa orientasi peserta didik baru (MOPD).
Langkah tersebut kemudian dikuatkan melalui Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 untuk tingkat sekolah, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 253/B/SE/VIII/2016, yang secara resmi mengubah nama kegiatan inisiasi mahasiswa baru menjadi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
Lebih lanjut, melalui Surat Edaran Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor: 468/B/SE/2017, PPKMB diharapkan membangun arti penting pendidikan, persahabatan, dan pengenalan lingkungan kampus kepada mahasiswa baru. Tentu saja, ia wajib dilandasi oleh prinsip persaudaraan dan anti kekerasan.
Meski telah berubah nama, budaya kekerasan dalam inisiasi mahasiswa baru masih tetap terjadi. Sebut saja, dua orang senior Universitas Negeri Surabaya (Unesa) membentak mahasiswa baru agar menunjukkan ikat pinggang mereka dalam kegiatan PKKMB. Aksi mereka berakhir viral di internet, dan melahirkan berbagai satir dan meme di tangan warganet yang kreatif.
Tidak lama setelah itu, tepatnya pada 2022, mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang tengah mengikuti PKKMB mengalami dehidrasi, karena dijemur di tengah lapangan. Seperti yang diungkapkan salah satu peserta, hal ini bisa membuatnya tipes kalau gini nahan lapar nahan haus.
Epilog: Menunggu Matahari Terbit dari Barat
Angin baru berembus, hinggap dalam paru-paru peserta didik dan mahasiswa baru yang sedang mengikuti kegiatan inisiasi. Namun, ia tak melulu sebuah hawa segar persahabatan, kebahagiaan, dan semangat untuk menggali sumur pengetahuan. Seringkali, ia datang sebagai angin busuk kekerasan dan senioritas.
Dua kasus yang terjadi di Unesa dan Untirta, ketika program inisiasi mahasiswa baru telah berganti identitas menjadi PPKMB, membuktikan bahwa tradisi periode ontgroening dan perpeloncoan masih eksis.
Tentu, para pemangku kebijakan, universitas/lembaga pendidikan, mahasiswa dan peserta didik, serta publik lainnya, berharap tradisi tersebut punah seiring dengan digunakannya nama PPKMB. Namun, ia sepertinya lebih tepat disebut sebagai sekadar ganti bungkus, alih-alih melakukan pengemasan ulang secara menyeluruh.
Mungkin, tradisi kekerasan dan senioritas dalam mengubah seorang mahasiswa yang masih groen menjadi ontgroen di negeri ini baru bisa lenyap setelah matahari terbit dari Barat.